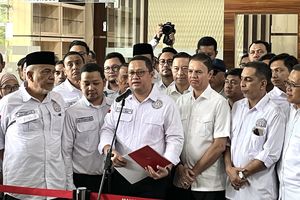Setiap malam menjelang tidur saya punya kebiasaan baru yang salah. Mendengarkan radio siaran swasta nasional yang selalu menampilkan berbagai narasumber dalam diskusi.
Sembilan puluh persen materi berputar di sekitar masalah pandemi yang sudah mulai menjengkelkan karena tak usai-usai.
Dan di antara pendengar yang ikut diskusi interaktif, cukup banyak yang merasa pandemi ini konspirasi tingkat tinggi orang kaya yang ingin semakin kaya dan yang miskin kian tertekan.
Sekali pun jam tidur saya agak mundur, bahkan terkadang malah sulit terlelap, saya semakin yakin bahwa edukasi soal pandemi ini sejak awal sudah salah kaprah.
Baca juga: Menyoal Otonomi Moral Pelaksanaan Protokol Kesehatan
Lebih konyol lagi, orang-orang yang tadinya saya pikir punya literasi mumpuni, ternyata demi ingin hidup seperti biasanya lalu terjebak dalam protokol konyol.
Ngotot menjalankan protokol, tapi tetap tertular. Bisa jadi mereka berpikir dari ketiga protokol itu cukup dijalankan salah satunya saja – seperti pilihan ganda soal ujian. Tak kurang menggelikannya, orang-orang ‘prominen’ ini rajin tes swab yang mahalnya ampun-ampun.
Bayangkan 1 manusia jika mau hasil ekspres harus menguras 1 juta lebih dari kantong (yang masih tebal barangkali).
Sementara jumlah yang sama bisa dibagi ke 3-5 keluarga setara bansos untuk menyambung hidup sebulan.
Bolak balik swab tes menandakan keraguan pelaksanaan protokol, sebab menyisakan risiko. Ibarat tidak menggunakan alat KB, tapi takut hamil – sementara hubungan seks jalan terus (inginnya seperti biasa). Lalu setiap sekian hari sekali ‘kepo’ mengecek dengan alat tes kehamilan.
Aneh bukan? Lebih aneh lagi protokol konyol ini menjadi ritual orang-orang berduit dan dalam versi lebih murah bernama rapid antigen - dipakai beberapa komunitas yang ‘rajin bikin acara’.
Sementara itu, ekonomi yang diharapkan bisa berjalan sejajar dengan kesehatan ternyata di lapangan tidak seindah yang direncanakan.
Pedagang pasar mengomel panjang lebar karena merasa diatur-atur sementara mereka merasa ‘baik-baik’ saja. Tidak ada sesama pedagang yang ketularan katanya.
Begitu pula pemilik lapak mewah yang istilahnya ‘mall’ berkeluh kesah sepi pengunjung dan penyewa minta negosiasi ongkos sewa.
Jam batas tutup pertokoan dan restoran yang maju mundur semakin memusingkan kepala. Apa bedanya tutup jam 21.00 atau 22.00?
Mengurus negri yang sudah ‘kepalang basah’ memang tidak mudah. Tren gaya hidup kita memang beda.
Di Perth Australia Barat, setiap hari toko tutup jam 5 sore dan hanya 1 hari dalam seminggu (bukan akhir minggu) istilah night shopping diberlakukan: toko tutup jam 21.00 di hari Kamis. Dan tak ada yang protes – karena sudah menjadi gaya hidup di sana.
Dengan demikian setiap orang tanpa kecuali punya waktu cukup untuk keluarga, mulai dari memasak hingga menangani semua pekerjaan rumah tangga – sebab punya pembantu di rumah bukan fenomena yang lazim. Bicara gaya hidup sehat, barangkali lebih masuk akal di sana. Sekaligus hemat.
Bukan maksud ingin melihat rumput tetangga yang lebih hijau, tapi justru Indonesia potensial untuk lebih maju dan lekas ‘naik kelas’ – jika saja rakyatnya sepakat untuk meningkatkan martabat.
Tapi alih-alih mudah diatur, anomali publik kita justru mau saling mengatur dan pantang ditegur.
Lebih ironinya lagi, merasa nyaman dengan situasi yang jelas-jelas menunjukkan kemunduran, terutama di sisi kesehatan.
Baca juga: Ketika Keterampilan Hidup Akan Menjadi Gaya Hidup