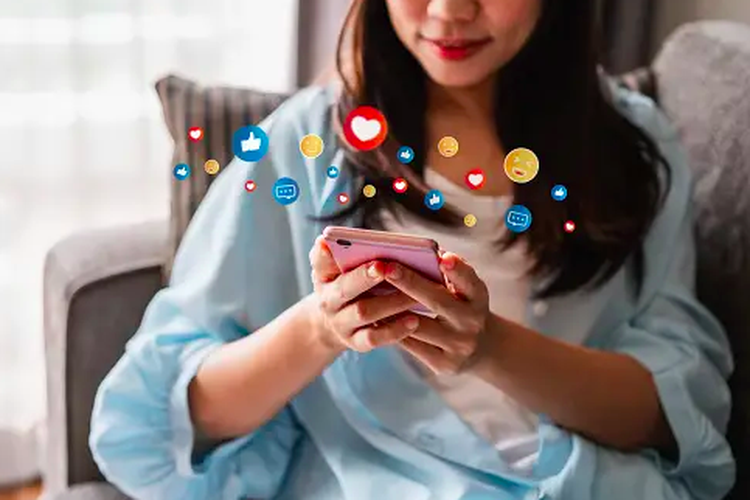Gen Z Terlalu Aktif Bicarakan Trauma di Media Sosial, Pahami Risikonya

KOMPAS.com - Berbagai upaya yang dilakukan Gen Z untuk menghilangkan stigma pada masalah kesehatan mental.
Hal itu pun membuat mereka semakin membuka diri di media sosial seperti TikTok, termasuk melampiaskan rasa sakit hingga cerita pengalaman trauma secara online.
Tren itu mulai mengalami peningkatan sejak enam bulan terakhir. Tidak sedikit Gen Z yang berani membuka pengalaman traumatisnya secara gamblang.
“Kami melihat orang-orang (anak muda) angkat bicara tentang penyerangan, baik secara seksual maupun fisik. Banyak pelecehan juga, segala jenis pelecehan mental, verbal, emosional dan fisik," kata Meg Schnetzer, seorang praktisi somatik yang mendalami seputar trauma.
Para ahli pun memuji kejujuran Gen Z dalam membagikan cerita traumatis, sebab hal itu bisa "menormalkan pembicaraan" hingga menginspirasi orang lain untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
"Tampaknya ada banyak kesadaran, sehingga mereka merasa cukup aman untuk membuka diri dan berbagi pengalaman mereka," jelas Schnetzer.
Baca juga: TikTok Jadi Media Pelampiasan Trauma di Kalangan Gen Z
Risiko oversharing cerita traumatis di media sosial
 Ilustrasi Gen Z melampiaskan trauma di TikTok
Ilustrasi Gen Z melampiaskan trauma di TikTokMeski terdengar sebagai langkah positif, tapi kata Schnetzer, transparansi seputar masalah kesehatan mental yang disebarluaskan sembarangan bisa memunculkan potensi berbahaya.
-
Pergeseran makna dari trauma itu sendiri
Kebebasan berbicara para Gen Z bisa mengarah pada penggunaan istilah yang keliru, seperti "gaslighting" atau makna dari "trauma" itu sendiri yang memungkinkan memanipulasi orang lain.
"Setiap orang mengalami trauma dan penyembuhan yang berbeda. Apa yang disebut traumatis bagi seseorang, belum tentu bagi orang lain. Itu sangat relatif," paparnya.
-
Stigma perawatan yang tidak jelas
Terkadang, Gen Z hanya berbicara tentang pengalamannya tanpa mengungkapkan solusi yang dia tempuh.
Atau bisa juga perawatan seputar trauma yang dialami kerap dicontoh orang lain, padahal metode pemulihan trauma dapat berbeda pada setiap individu.
Konten-konten seperti ini juga dapat mengacaukan stigma seputar perawatan kesehatan mental yang tepat.
Schnetzer menjelaskan, dukungan saat mengalami pengalaman traumatis dapat menimbulkan dampak di kemudian hari.
"Saya yakin, tidak ada seorang pun yang luput dari trauma, karena trauma dapat berbeda bagi setiap orang."
"Sebagian orang bahkan tidak menyadari kalau mereka telah melaluinya," paparnya.
-
Dampak bagi prospek pencarian kerja
Para ahli telah memperingatkan tentang bahaya berbagi emosi secara berlebihan di media sosial, karena bisa berdampak pada prospek karier terutama saat mencari kerja.
Sebuah penelitian terbaru menemukan, orang yang kerap berbagi cerita tentang perjuangan menghadapi kesehatan mental di LinkedIn, dapat membuatnya terlihat sebagai kandidat yang kurang stabil secara emosional di mata calon bos atau rekruter.
Fakta penelitian itu pun sebenarnya cukup disayangkan oleh Schnetzer. Sebab menurutnya, pengalaman traumatis sebaiknya tidak dipandang sebagai "identitas seseorang" dan itu hanyalah bagian dari pengalaman hidup mereka.
"Menyedihkan, saya yakin tidak ada yang berbagi berlebihan. Menurut saya, orang lain mungkin hanya merasa tidak nyaman dengan trauma atau pengalaman yang kita alami."
"Sejujurnya saya sangat merasa sedih melihat fakta yang terjadi, ketika kandidat tidak jadi dipekerjakan hanya karena mereka berani berbicara tentang sesuatu yang sulit dan bukan kesalahan mereka," tutupnya.
Baca juga: 5 Aksi Sederhana yang Bisa Dilakukan Generasi Z untuk Lawan Polusi
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang